
Oleh: Diaz Hamzah
Dulu, membuka Google di ponsel terasa seperti menyaksikan keajaiban kecil. Layar hitam-putih Nokia, tombol fisik yang keras, dan koneksi GPRS yang tersendat. Satu halaman web bisa memakan waktu hingga tiga puluh detik untuk tampil sempurna, dengan gambar yang turun perlahan, seolah dijatuhkan satu per satu dari langit. Mengunduh lagu MP3 berukuran tiga megabyte? Bersiaplah menunggu satu jam, itu pun jika koneksi tidak putus di tengah jalan. Lambat, sering menjengkelkan, tetapi entah mengapa tetap membahagiakan. Itulah masa 2G, ketika internet masih terasa asing, baru, dan penuh harapan.
Generasi kedua teknologi seluler ini hadir dengan misi sederhana: menelepon dan mengirim SMS. Tanpa tuntutan rumit, tanpa ekspektasi berlebihan. Justru karena kesederhanaannya, 2G menjadi sangat efisien. Baterai ponsel bisa bertahan berhari-hari, perangkatnya murah, dan infrastruktur jaringannya relatif sederhana. Hingga hari ini, 2G masih hidup, terutama di daerah pedalaman dan pada perangkat-perangkat khusus seperti mesin EDC, pelacak GPS, sistem alarm, hingga meteran listrik.
Di pertengahan 2000-an, 3G lahir sebagai lompatan besar. Internet mobile naik kelas. Waktu unduh menyusut drastis. Panggilan video mulai dikenal. BlackBerry Messenger merajai percakapan. Kita pun berkenalan dengan kebiasaan baru: menggulir layar tanpa henti. Smartphone meledak. iPhone generasi pertama hadir pada 2007, dengan 3G sebagai tulang punggungnya. Warnet (Warung Internet) perlahan ditinggalkan, dunia pindah ke genggaman tangan.
Namun, di balik gemerlap itu, tersembunyi masalah yang jarang dibicarakan: 3G boros dan tidak efisien. Ia membutuhkan spektrum lebar, infrastruktur kompleks, serta konsumsi listrik besar, namun hasilnya tidak sepadan. Ibarat mobil bertubuh besar yang minum bensin banyak, tetapi kecepatannya biasa saja.
Memasuki dekade 2010-an, 4G LTE hadir sebagai revolusi sesungguhnya. Kecepatannya melesat puluhan kali lipat. Streaming video HD menjadi lancar, game online stabil, dan panggilan video kian jernih. Yang terpenting, 4G jauh lebih efisien. Dengan spektrum yang sama, ia mampu mengirim data berkali-kali lipat dibandingkan 3G. Dari kendaraan boros, dunia beralih ke mesin yang lebih cepat dan lebih irit.
Kini, 5G berdiri di garis depan masa depan: super cepat, latensi rendah, dan sanggup menghubungkan jutaan perangkat sekaligus. Tetapi setiap teknologi baru selalu datang dengan satu kenyataan yang sama, ruang terbatas. Spektrum frekuensi tidak bertambah; ia ibarat tanah di tengah kota. Jika ingin membangun gedung baru, bangunan lama harus dibongkar.
Pertanyaannya kemudian muncul: bangunan mana yang harus dilepas? Mengapa bukan 2G yang lebih tua, melainkan justru 3G yang “dipensiunkan” lebih dulu?
Jawabannya terletak pada frekuensi dan nilai. 2G umumnya beroperasi di frekuensi rendah, seperti 900 MHz. Jangkauannya luas, mampu menembus medan sulit, dan sangat efisien untuk cakupan area besar. Sebaliknya, 3G banyak menggunakan pita 2100 MHz, frekuensi “emas” yang seimbang antara jangkauan dan kapasitas. Pita ini jauh lebih bernilai jika dialokasikan untuk 4G atau 5G. Dengan ruang yang sama, operator bisa membangun “bangunan” bertingkat: kapasitas lebih besar, layanan lebih cepat. Ibarat membandingkan rumah satu lantai dengan rumah tiga lantai di atas lahan yang sama.
Dari sisi bisnis, gambarnya semakin jelas. 2G murah untuk dirawat. Pendapatannya mungkin kecil, tetapi stabil dan tetap menguntungkan. Sebaliknya, 3G menelan biaya operasional tinggi: boros listrik, perawatan rumit, sementara penggunanya terus menurun karena beralih ke 4G. Ia menjadi beban, biaya besar, hasil sedikit.
Perangkat pun ikut berbicara. Miliaran perangkat di dunia masih bergantung pada 2G: ponsel sederhana milik lansia, mesin pembayaran, sistem keamanan, hingga perangkat IoT. Bahkan banyak ponsel modern masih mendukung 2G dan langsung melompat ke 4G atau 5G, melewati 3G sepenuhnya. Mematikan 2G berarti menciptakan gunung sampah elektronik dan potensi krisis sosial. Mematikan 3G? Dampaknya relatif jauh lebih kecil.
Lebih dari itu, 3G kehilangan identitas. 2G punya peran jelas: komunikasi dasar, jangkauan luas, dan murah. 4G dan 5G pun jelas: cepat, modern, dan berkapasitas besar. Sementara 3G terjepit di tengah, tidak sesederhana 2G, tidak secepat 4G. Semua yang bisa dilakukan 3G, kini dilakukan lebih baik oleh generasi lain. Ia seperti anak tengah dalam keluarga teknologi: ada, tetapi tak lagi dibutuhkan.
Bayangkan sebuah garasi dengan ruang terbatas. Di dalamnya ada sepeda tua yang tak butuh bahan bakar, mobil harian yang efisien, kendaraan listrik untuk masa depan, dan satu motor lama yang boros serta jarang dipakai. Saat harus memilih, keputusan hampir selalu sama: motor itulah yang dilepas.
Begitulah nasib 3G. Keputusan mematikannya bukan keanehan, melainkan hasil perhitungan rasional: melepas yang paling tidak relevan demi manfaat yang lebih besar. Spektrum dibebaskan, efisiensi meningkat, dan mayoritas pengguna diuntungkan.
Lalu, kapan 2G akan menyusul? Bukan dalam waktu dekat. Bisa lima, sepuluh, bahkan lima belas tahun lagi di beberapa negara. Sebelum itu, dunia harus benar-benar siap dengan pengganti yang matang (seperti NB-IoT, Cat-M, atau 5G RedCap) agar kesederhanaan dan keandalan 2G tidak hilang tanpa solusi.
Pada akhirnya, kisah pensiunnya 3G mengingatkan kita satu hal: dalam arus kemajuan, yang bertahan bukan selalu yang paling muda atau paling tua, melainkan yang paling relevan. Di hadapan zaman yang terus berlari, 3G pun berhenti, bukan karena gagal, melainkan karena tak lagi diperlukan.

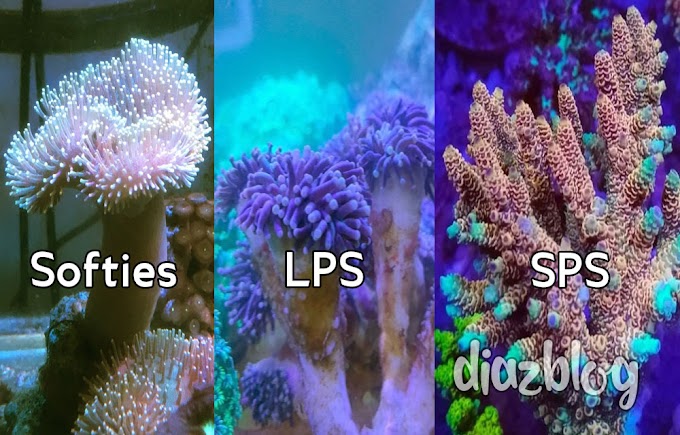



0 Komentar